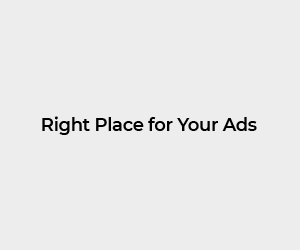Tulisan Abd. Rasyid, SH
(Ketua DPD PKS Kab Donggala)
Sejak didengungkan efisiensi maka saat itu semua terperanjat karena tetiba semua merasa “kehilangan” dan merasa tidak ada harapan. Efisiensi langsung dihakimi sebagai pemangkasan atau pemotongan. Padahal jika melihat dalam KBBI bahwa defenisi Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.
Berarti efisiensi pada dasarnya punya alat ukur yang sederhana yaitu ketepatan (Tepat waktu, tepat tenaga dan tepat biaya). Artinya secara ideal jargon efisiensi sangatlah tepat dipakai untuk apa saja dan oleh siapa saja, apalagi jika berkaitan dengan urusan pemerintahan.
Jika demikian adanya, mengapa justru efisiensi dianggap oleh sebagian pejabat sebagai sebuah krisis? Atau semacam kampanye pemotongan sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat optimal bekerja. Benarkah demikian?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi pejabat seringkali diasosiasikan dengan memiliki akses berlebih—anggaran yang besar, serta fasilitas yang terkadang jauh melampaui kebutuhan pokok untuk mencapai tujuan organisasi.
Budaya kerja yang mapan, yang seringkali cenderung inklusif terhadap pemborosan, telah menciptakan zona nyaman yang sulit ditinggalkan. Dalam kerangka berpikir ini, efisiensi dianggap sebagai “ancaman” karena secara langsung menantang dan memangkas kelebihan-kelebihan tersebut.
Efisiensi dan Rasionalitas Administrasi
Secara ilmiah, efisiensi berkaitan erat dengan konsep Rasionalitas Administrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu mencapai tujuan organisasi dengan cara paling ekonomis. Di sektor publik, hal ini berarti memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya (APBN/APBD) seminimal mungkin.
Masalahnya adalah, ketika pejabat mendengar kata efisiensi, yang terbayang bukanlah optimasi proses kerja (misalnya, memangkas birokrasi yang panjang atau mengintegrasikan sistem digital), melainkan sekadar pemotongan anggaran belanja barang atau kegiatan rutin. Pemotongan memang merupakan salah satu wujud efisiensi, tetapi bukan intinya. Inti dari efisiensi adalah perubahan gaya kerja dari output-oriented (sekadar menghabiskan anggaran) menjadi outcome-oriented (mencapai hasil nyata bagi publik dengan biaya minimal).
Paradigma yang Perlu Diubah yaitu Dari “Banyak Lebih Baik” menjadi “Cerdas Lebih Efektif”
Efisiensi sejatinya membutuhkan tiga pilar perubahan:
- Perubahan Mindset (Pola Pikir): Menggeser pandangan dari “anggaran adalah hak” menjadi “anggaran adalah amanah dan alat ukur kinerja.” Pemborosan harus dianggap sebagai kegagalan administrasi, bukan kelaziman.
- Perubahan Proses (Tata Kelola): Menerapkan teknologi untuk mendigitalkan proses, menghilangkan duplikasi kerja, dan merasionalisasi jumlah rapat, dokumen, serta kegiatan yang tidak substansial. Ini adalah efisiensi struktural.
- Perubahan Alat Ukur (Akuntabilitas): Memperkenalkan metrik kinerja yang tidak hanya mengukur serapan anggaran, tetapi juga dampak nyata dan rasio biaya-manfaat (Cost-Benefit Ratio).
Jika efisiensi hanya diterjemahkan sebagai krisis pemotongan, maka hasilnya adalah kontra-produktif: kualitas kerja menurun karena sumber daya utama (tenaga) dipangkas tanpa memperbaiki proses. Sebaliknya, jika efisiensi diartikan sebagai reformasi gaya kerja maka itu akan menjadi motor penggerak optimasi birokrasi.
Oleh karena itu, bagi para pejabat, efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti bekerja optimal. Sebaliknya, ini adalah tantangan intelektual dan manajerial untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengelola sumber daya publik dengan ketepatan dan akuntabilitas yang tinggi.
Efisiensi adalah panggilan untuk meninggalkan gaya kerja lama yang berbiaya tinggi menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, ramping, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Dengan merangkul prinsip ini, efisiensi akan berubah dari momok menjadi motor inovasi.
Wallahu a’lam bishhawab
Maleni 3 November 2025
Dari Sudut Lapangan Persido